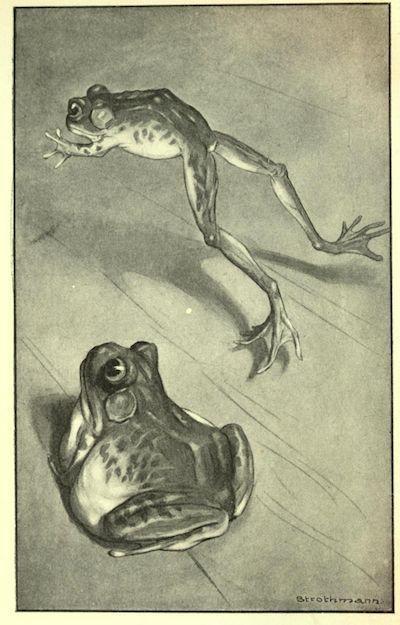|
| image |
Kakek bisa membelah diri. Bisa berada di banyak tempat sekaligus….
Aku melihat Kakek tengah berdiri memandang keluar jendela, ketika aku masuk. Kamar gelap—mungkin Kakek sengaja mematikan lampu—aku merasa ia tak ingin diganggu. Pelan pintu aku tutup kembali. “Masuklah,” suara Kakek lemah. Ia tergolek, dengan selang oksigen dan infus yang bagai mencencangnya di ranjang. Demi Tuhan! Aku tadi melihat Kakek berdiri dekat jendela itu. Benarkah Kekek bisa berpindah dalam sekejap?
Kurasakan, Kakek mengedipkan mata: sini, tak usah heran begitu. Padahal kulihat ia terbaring memejamkan mata begitu tenang.
Dua hari sebelum puasa, ibu menelepon. Kakek jatuh di kamar mandi, serangan jantung. Mas Jo memintaku segera saja ke Jakarta. Sebelum terlambat—ia rupanya tahu keenggananku menjenguk Kakek. “Biar aku urus Nina,” katanya. Bungsuku itu memang baru kena demam berdarah.
Aku tak terlalu dekat dengan Kakek. Bahkan tak menyukainya. Semasa kecil, kakak-kakak dan sepupuku suka sekali mendengarkan cerita Kakek. Duduk mengelilingi dan bergelendotan manja setiap Kakek bercerita tentang burung-burung cahaya yang terbang dari surga membawa biji-biji kebaikan, ular berkepala lima, makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan, angsa yang menyelam ke dasar samudera atau Nabi Sulaiman yang mendengarkan percakapan cicak dan buaya.
Itu bohong, kataku, setiap Kakek bertanya kenapa aku tak suka ceritanya. Aku lebih suka belajar matematika. Bagiku Kakek tak lebih tukang khayal. Dan khayalan itu penyakit yang gampang menular. Penyakit orang malas, kata Nenek. Aku memang tak suka setiap melihat Kakek hanya duduk-duduk dikelilingi para kakak dan sepupuku—seperti sekumpulan orang malas yang seharian hanya bercanda—sementara Nenek di dapur sibuk membuat kue. Aku lebih suka menemani Nenek di dapur, mencicipi remah kue yang dibikinnya, dan selalu merasa begitu bangga ketika Nenek memberikan padaku potongan kue yang lebih besar.
Tapi kakak-kakak dan sepupuku bilang, Kakek punya kue yang jauh lebih lezat dari kue bikinan Nenek. Kue itu kue yang dihidangkan ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Seperti apem, tetapi bagai terbuat dari cokelat. Kue itu tak akan habis bila dimakan. Aku benci mendengar cerita itu. Benar, khayalan memang penyakit menular. Kupikir mereka sudah tertular khayalan Kakek.
Aku ingat setelah kejadian itu, tengah malam, antara tidur dan jaga, entah mimpi entah nyata, aku melihat Kakek duduk di sisi ranjangku, sembari makan kue pelan-pelan. “Mau?” ia menawariku. Seolah ada gerak yang mendorong tanganku untuk mengambil kue itu, memakannya. Rasa kue itu jauh lebih enak dari kue buatan Nenek
.
***
Kakek pingin ketemu kamu, kata ibu di telepon. Yakin, pasti Kak Sofyan yang menyuruh. Kakek tinggal bersama kakak keduaku itu, dan ia tahu aku pasti mau mendengarkan bila yang menelepon ibu.
“Kenapa kamu tak suka Kakek?” dulu, ibu bertanya. Aku terus pura-pura membaca.
Suaranya lembut, membuatmu merasa tenteram setiap mendengarkannya bercerita. Matanya keteduhan yang ingin kau jumpai. Nyaris tak pernah marah. Dan—ini yang menurut kakak-kakak dan sepupuku paling disukai dari Kakek—tak suka cerewet memberi nasehat. Rasanya tak ada alasan untuk tidak menyukainya.
Mungkin karena iri. Atau tak mau berbagi. Kakek membagi perhatian pada semua cucunya. Aku selalu ingat pada kejadian saat suatu kali Kakek membawa martabak. Kakek membagi rata buat semua cucunya. Semua gembira.
Tapi aku segera pergi. Aku ingin Kakek seperti Nenek! Bila punya kue, aku selalu dapat bagian lebih banyak. Aku senang bila kakak dan sepupu menatap iri bagian kue yang lebih besar milikku. Itulah saat-saat paling membahagiakan buatku. Nenek mengerti kebahagiaanku itu. Kakek tidak.
Itulah sebabnya aku tak pernah terlalu suka Kakek. Tak pernah bisa merasa dekat.
Tapi Kakek ingin sekali ketemu kamu, kata ibu saat menelepon. Dan ibu bilang: Dua hari di rumah sakit, Kakek bersikeras pingin pulang. Rumah sakit hanya membuat kita benar-benar merasa sakit, keluh Kakek. Para suster mengatakan kalau Kakek adalah pasien paling tak bisa diatur. Tak mau minum obat, dan tak mau disuruh diam. Dia suka sekali mendongeng dan cerita, kata seorang suster. Pernah, malam-malam, Kakek memanggil suster jaga, hanya karena ia mau bercerita kalau baru saja ada lima laki-laki menjenguknya.
“Mereka tinggi besar dan bersayap. Mereka memijiti jempol saya, dan bilang saya tak apa-apa. Suster lihat, kan… tadi mereka masuk ke sini? Lima laki-laki tinggi besar bersayap…,” kata Kakek. Suster hanya diam. Karena suster itu memang tak melihat siapa-siapa memasuki kamar ICU. “Mereka memberi saya ini,” Kakek memperlihatkan sebutir kurma. Kurma nabi, kata Kakek.
***
Aku teringat beberapa tahun lalu.
Mbak Rin, istri Mas Moko, kakak sulungku, mengalami masalah persalinan. Bayinya melintang, kata dokter, dan harus operasi. Lalu Kakek muncul, memberinya sebutir kurma. Mbak Rin yang sudah terlihat lelah dan pasrah, perlahan tak lagi merasa kesakitan. Kemudian melahirkan dengan lancar.
Pernah pula Tante Ida, yang tinggal di Jombang, menelepon malam-malam: Kakek barusan datang menjenguk anaknya yang panas. Kakek mengusap keningnya, kemudian pergi. Dua jam setelahnya panas Ibra berangsur lenyap. Sumpah, sepanjang malam itu, aku melihat Kakek hanya duduk sambil tiduran di kursi goyangnya.
Kakek bisa berada di dua tempat sekaligus, kata Einda. Ia bisa muncul begitu saja saat kita membutuhkan. Lalu sepupuku itu bercerita, betapa pernah suatu kali ia sakit dua hari sebelum ujian kelulusan SMA. Kakek tiba-tiba muncul di kamar kosnya, memberinya segelas air putih, dan ia tertidur. Saya bermimpi berada di tempat yang begitu tenang dan nyaman. Besok paginya saya sudah bugar!
Semasa kanak, kakak-kakakku juga sering bercerita kalau Kakek kerap muncul malam-malam di kamar, memberi mereka eskrim atau cokelat. Eskrim dan cokelat itu, tiba-tiba saja sudah ada di tangan Kakek.
“Sulap! Itu sulap,” kataku.
“Itu mukjizat,” kata mereka, “Kakek berbakat jadi nabi.”
Kakek terkekeh ketika mendengar itu. “Jangan pernah punya cita-cita jadi nabi,” katanya. “Tidak enak jadi nabi. Karena tidak semua orang menyukai.”
***
Kalau punya mukjizat, pastilah Kakek tak tergolek seperti ini—seolah suara dari masa kecilku muncul kembali. Tubuh Kakek terlihat begah dan membengkak. Seperti ada tumpukan jerami yang dimasukkan ke dalam perut dan dadanya. Seolah seluruh makanan yang selama ini disantapnya dijejalkan semuanya ke tubuh Kakek. Tongseng, sate klatak, empal, paru, kikil dan sop buntut, kepala kambing bacem, gulai, dan tengkleng….
Bahkan seorang nabi pun pernah sakit—aku seperti mendengar suara berbisik di belakangku. Aku bisa merasakan napas lembut merambati tengkukku. Aku yakin ada seseorang berdiri di belakangku. Kakek?
Tidak. Kulihat Kakek terbaring di ranjang. Akankah ia sebentar lagi mati? Bila iya, bahkan menjelang kematiannya pun wajahnya tak berubah: terlihat bersih. Sepanjang yang saya ingat, wajah Kakek memang nyaris tak pernah berubah. Seperti tak tersentuh usia. Sampai saat ini wajahnya masih wajah yang aku kenal saat aku kanak-kanak: sekilas terasa jenaka karena suka tertawa, rambutnya putih, juga alisnya. Ia tak memelihara jenggot dan kumis. Klimis. Matanya bening bulat, mata yang selalu gembira. Wajah agak bundar. Dengan tahi lalat mirip butir beras ketan hitam di dahi kiri. Ketika Nenek mulai sakit-sakitan, Kakek seperti tak berubah. Ada yang bilang karena Kakek punya kesaktian. Tetapi seingatku tak ada yang aneh dari keseharian Kakek. Ia tak suka kungkum atau nyepi untuk semedi. Tak kulihat ia melakukan ritual-ritual mistis tertentu. Pati geni atau sejenisnya. Tak pernah kulihat ia sibuk dengan jimat atau barang-barang pusaka keramat. Bahkan, di banding Nenek, Kakek termasuk tak rajin ibadah. Saat waktu salat, malah sering kulihat Kakek tetap duduk-duduk klempas-klempus menikmati rokoknya.
“Ibadah Kakek ya berbuat baik… itu saja,” pernah kudengar ia bicara begitu saat ditanya sepupuku.
Kupandangi wajah Kakek. Seperti ingin belajar mengenalnya kembali.
“Kau tahu…,” kudengar ia bergumam, matanya masih memejam. Aku kaget, menyangka ia tidur. “Kau tahu, kenapa kita membutuhkan orang lain? Karena dokter pun tak bisa mengobati dirinya sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, itulah kenapa kita mesti baik pada orang lain.”
Jari-jari gemetar Kakek menyentuh lenganku.
“Terima kasih mau datang.”
Ada yang jauh lebih dalam dari kepedihan.
“Aku selalu melihat ada yang berkelebat, di luar sana. Menunggu di sebalik jendela. Dan tadi…. Tadi kulihat ia berdiri di belakangmu….”
Kugenggam tangan Kakek.
“’Lihatlah….” Pandangannya mengarah jendela, dan entahlah, seperti ada tangan gaib yang perlahan memaksaku menoleh. Kesiur angin menerobos, korden bergoyang dan sekelebat bayangan merambat gelap. Tak kulihat apa-apa. Selain tugur pepohonan dan bentangan kesunyian. Cahaya terasa lamur.
“Maukah kau kali ini, mendengarkan ceritaku?”
Suaranya memelan. Aku membungkuk, ke arah bibirnya, takut tak mendengar kata terakhirnya.
Dengarlah, mereka mendekat….
Rasa kantuk seperti angin lembut. Suara Kakek menjauh, tinggal dengung AC memenuhi ruangan. Aku meriap merasakan ada yang perlahan masuk melalui jendela. Pastilah aku tak lagi mampu menahan kantuk dan lelah, sampai kurasakan ada tangan halus mengusap wajahku, membangunkanku.
Ia tampak letih. Berdiri di bawah pohon putih, yang menjulang hingga ke langit warna ganih. Pandanganku seketika terpesona pada bayi-bayi bersayap jelita yang bermunculan dari balik cakrawala. Bayi-bayi itu terbang mengitari Kakek yang melangkah pelan menuju batu besar. Bayi-bayi bersayap jelita memberi isyarat agar Kakek berbaring, sementara angin sejuk berhembus dari sayap-sayap lembut itu.
Aku menyaksikan bayi-bayi itu membedah dada Kakek, mengeluarkan jantungnya. Ada bejana kecil, dan bayi-bayi itu mencuci jantung Kakek. Aku memejam, merasakan tubuhku melayang. Seperti memasuki rongga sunyi. Merasakan tidur panjang abadi.
***
Hari masih gelap—atau telah kembali gelap?—ketika aku terbangun oleh suara-suara percakapan. Sayup-sayup terdengar suara orang mengaji. Seperti suara ibu. Aku mencoba mengenali sekeliling. Kekelaman yang bagai tabir berlapis-lapis. Setiap suara seperti merembes dari tabir yang berbeda-beda. Kulihat arak-arakan orang membawa keranda, menjauh. Jeritan yang bagai jerit iblis. Bau harum melati mengapung. Kusaksikan beberapa suster yang sibuk memberesi tabung oksigen dan membawa keluar kereta dorong, kemudian lenyap begitu saja, raib ke sebalik tabir kegelapan yang hampa. Ranjang itu kosong. Pasti mereka telah membawa Kakek ke kamar mayat. Aku berlari, melesat—seakan melangkah di hamparan awan—sampai kelelahan dan lesap dalam gelap.
Aku terbangun seperti orang yang telah berabad-abad ditidurkan.
Kudapati ibu, Mas Jo dan istrinya, Mbak Rin, Mas Moko, Einda, dan hampir seluruh kerabatku menggerombol berbincang pelan. Pelan-pelan aku mulai mengenali, di mana aku berada: kamarku.
Ibu pelan-pelan memelukku. Aku terisak. Saat itulah, aku mendengar suara tawa Kakek.
Aku hanya bengong ketika ibu bercerita keadaan Kakek. “Kau kira Kakek mati, ya?”
Adakah ini mukjizat….
“Dokter juga heran dengan jantung kakek. Tiba-tiba sudah bersih, seperti baru dicuci….”
Di ruang ten
gah kulihat Kakek tertawa-tawa gembira dikerubuti tujuh keponakanku yang tampak bagai segerombolan kurcaci. Lama aku terdiam memandanginya. Aku seperti mendengar kelepak sayap bayi-bayi itu terbang menjauh.
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga memberi manfaat. Baca juga cerpen Hujan Mulai Deras, Malam