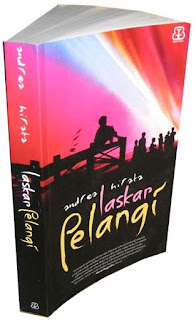|
| image Red Mittens |
Kalian harus demokratis. Baik, tapi jauhkan
tinju yang kau kepalkan itu dari pelipisku
bukankah engkau… Tutup mulut! Soal tinjuku
mau kukepalkan, kusimpan di saku
atau kutonjokkan ke hidungmu,
tentu sepenuhnya terserah padaku.
Pokoknya kamu harus demokratis. Lagi pula
kita tidak sedang bicara soal aku, tapi soal kamu
yaitu kamu harus demokratis!
Tentu saja saya setuju, bukankah selama ini
saya telah mencoba… Sudahlah! Kami tak mau dengar
apa alasanmu. Tak perlu berkilah
dan buang waktu. Aku perintahkan kamu
untuk demokratis, habis perkara! Ingat
gerombolan demokrasi yang kami galang
akan melindasmu habis. Jadi jangan macam-macam
Yang penting kamu harus demokratis.
Awas kalau tidak!
SINGER
Seorang lelaki
berkutat bebaskan budak
dalam diri,
menulis musuh
dalam kisah cinta sejati.
Tapi trauma dan masa lalu
bagai mantan istri
yang selalu memaksa
untuk rujuk kembali.
Dalih adalah Sang Tuan
dari rembang ingatan.
Bahkan di detik jingga
di nadi hidup
yang berdegup mesra,
selalu ada dalih bagi kita
untuk tetap tak bahagia.
SARTRE
Neraka keberadaan tak lain
adalah orang lain, ucapmu
dalam sebuah pintu tertutup
pada sebuah drama canggung
dari sebuah zaman yang murung.
Di tanah airku, ada dan ketiadaan
karcis menjadi tema utama
setiap hari raya. Stasiun dan terminal
tersengal oleh antrian: panjang
dan rapat seperti kalimat filsafat.
Kerumunan yang berdebar
tak sabar ingin memudikkan jiwa
dan badan ke surga kebersamaan
kerabat dan keluarga
karena neraka tak lain
adalah tanpa orang lain.
Neraka keberadaan tak lain
adalah orang lain, ucapmu
dalam sebuah pintu tertutup
pada sebuah drama canggung
dari sebuah zaman yang murung.
Di tanah airku, ada dan ketiadaan
karcis menjadi tema utama
setiap hari raya. Stasiun dan terminal
tersengal oleh antrian: panjang
dan rapat seperti kalimat filsafat.
Kerumunan yang berdebar
tak sabar ingin memudikkan jiwa
dan badan ke surga kebersamaan
kerabat dan keluarga
karena neraka tak lain
adalah tanpa orang lain.
CHAIRIL
Pada kereta senja
Chairil menebal jendela
cinta dan bahagia
makin jauh saja
mendengking Chairil
mendengking kereta
sayatan terus ke dada.
Pada senja di pelabuhan kecil
kau datang padaku: Chairil
cinta insani di tangan kiri,
Amir Hamzah cinta Ilahi
di tangan kanan
dengan pandang memastikan
: untukku. Aku membisu
dicakar gairah dan cemas
bertukar tangkap dengan lepas.
Aku hilang bentuk
remuk. Seharian itu
kita tak bersapaan. Oh puisi
yang enggan memberi
mampus kau
dikoyak-koyak sepi.
Kekasih, dengan apakah
kita perbandingkan pertemuan kita
: dengan Amir sepoi sepi
atau Chairil menderai sampai jauh?
Kini habis kikis segala cintaku
hilang terbang, kembali sangsai
seperti dahulu di nyanyi sunyi
di buah rindu.
Amirlah kandil kemerlap
pelita Chairil di malam gelap
ketika dada rasa hampa
dan jam dinding yang berdetak.
Aku sendiri, menyusur kata-kata
masih pengap harap. Apatah kekal
kekasihku, airmata yang kenduri
di riuh nadi di gamang jiwa
sedang cerlang matamu
tinggal kerlip puisi
di malam sunyi.
Chairil dan Amir
di pintumu puisi negeriku mengetuk.
Mereka tak bisa berpaling.
CERVANTES
Dengan pena terhunus kau pacu keledai sastra
menerjang kincir keramat hikayat bangsawan
dan raja-raja hingga porak-poranda
dan menjelma jadi gelak tawa
Di negeri-negeri yang jidatnya sempit
dan muram, tank, panser, dan penjara
tersedia bagi Don Quixote dan keledai sastra
yang menggoyang kebajikan mapan
bungkus mulia bagi jiwa-jiwa deksura.
Adakah ksatria gelak tawa berbahaya
bagi negara, serupa ular berbisa di belukar
mendesis merayap menyusun makar?
Dia yang bijaksana tahu tak ada
mahkota dimakzulkan oleh cerita
jika ke dalamnya penguasa sedia berkaca.
Keledai sastra yang dungu bestari
senantiasa menggergaji satu kaki singgasana
agar sang raja belajar bijaksana di atasnya.
Atau mengecat tembok istana
dengan warna ganjil tak biasa
biar angker kekuasaan sedikit belajar
menertawakan diri dan agak jenaka.
Dengan pena terhunus kau pacu keledai sastra
menerjang kincir keramat hikayat bangsawan
dan raja-raja hingga porak-poranda
dan menjelma jadi gelak tawa
Kisah sehari-hari dan orang biasa
sejak itu berhak juga menjelma cerita.
Dengan pena terhunus kau pacu keledai sastra
menerjang kincir keramat hikayat bangsawan
dan raja-raja hingga porak-poranda
dan menjelma jadi gelak tawa
Di negeri-negeri yang jidatnya sempit
dan muram, tank, panser, dan penjara
tersedia bagi Don Quixote dan keledai sastra
yang menggoyang kebajikan mapan
bungkus mulia bagi jiwa-jiwa deksura.
Adakah ksatria gelak tawa berbahaya
bagi negara, serupa ular berbisa di belukar
mendesis merayap menyusun makar?
Dia yang bijaksana tahu tak ada
mahkota dimakzulkan oleh cerita
jika ke dalamnya penguasa sedia berkaca.
Keledai sastra yang dungu bestari
senantiasa menggergaji satu kaki singgasana
agar sang raja belajar bijaksana di atasnya.
Atau mengecat tembok istana
dengan warna ganjil tak biasa
biar angker kekuasaan sedikit belajar
menertawakan diri dan agak jenaka.
Dengan pena terhunus kau pacu keledai sastra
menerjang kincir keramat hikayat bangsawan
dan raja-raja hingga porak-poranda
dan menjelma jadi gelak tawa
Kisah sehari-hari dan orang biasa
sejak itu berhak juga menjelma cerita.
PAMUK
Adalah salju
yang mempertemukan
orang sunyi dengan puisi
ketika perempuan yang tertindas
menghidupkan emansipasi
dengan bunuh diri
Bisakah manusia bahagia
sebagai pasangan cinta
menghuni rumah mungil berdua
tanpa direcoki perabot-perabot berat
dan sulit diangkat seperti negara
atau perkakas keras
tajam dan bergerigi
seperti ideologi?
Di Kars atau Tanjung Priok
di Kabul atau Istambul, sandiwara
bisa saja mengkudeta fakta
ketika remaja-remaja yang rindu
dan mereka yang mengusir pilu
dalam sebuah pertunjukan
terburai diserbu serdadu
hanya karena seorang komandan
yang bosan dan putus asa
mendadak ingin jadi sutradara.
Namaku merah, seperti darah
warna termegah dalam sejarah.
layar terpintal di sunyi Pamuk
membungkus puing-puing Attaturk
Negeri-negeri salju kastil-kastil kertas
sejarah mengeras di tapal batas
hari-hari timur hari-hari barat
hamba dan tuan bertukar tempat.
Musim mengeras di tapal batas.
Ada yang diam-diam bergegas
melaju di atas seribu bus seperti Pamuk
atau Osman atau Mehmet atau kau
memburu cinta, kematian, atau malaikat
dan tak mendapat apa-apa kecuali
identitas yang meranggas dan sekarat
antara masa kanak yang terkoyak
dan masa depan yang lembam.
Antara timur yang mendengkur
dan barat yang berkarat.
Dari Herat menuju ke Barat
merana tersungkur di Indonesia
ingatan adalah rakyat berkarat
menetas sia-sia dari telur amnesia.
Sambil menyusuri kota kelahiran
dalam ingatan silam, ditentengnya hidup baru
seperti menenteng kopor ayah
tempat istana salju dan buku hitam catatan harian
menyembul diam-diam bagai kenangan:
bacaan-bacaan masa muda
yang menggendong sukma ke Eropa,
dan hikayat-hikayat keramat
yang menuntun gelisah
kembali pulang ke rumah.
Di luar masih terhampar
dunia-dunia yang membenci
sebesar mencinta, yang bercumbu
sekerap bertengkar, bagai hujan salju
yang indah dan memisah hingga selalu susah
untuk bertegur sapa. Tapi akan selalu ada
yang sabar seperti Orhan, menyalakan lilin
untuk mencairkan salju yang membeku
di jembatan perjumpaan
biar segala yang lindap dan tak terucap
dapat bersijingkat temukan jalan.
Adalah salju
yang mempertemukan
orang sunyi dengan puisi
ketika perempuan yang tertindas
menghidupkan emansipasi
dengan bunuh diri
Bisakah manusia bahagia
sebagai pasangan cinta
menghuni rumah mungil berdua
tanpa direcoki perabot-perabot berat
dan sulit diangkat seperti negara
atau perkakas keras
tajam dan bergerigi
seperti ideologi?
Di Kars atau Tanjung Priok
di Kabul atau Istambul, sandiwara
bisa saja mengkudeta fakta
ketika remaja-remaja yang rindu
dan mereka yang mengusir pilu
dalam sebuah pertunjukan
terburai diserbu serdadu
hanya karena seorang komandan
yang bosan dan putus asa
mendadak ingin jadi sutradara.
Namaku merah, seperti darah
warna termegah dalam sejarah.
layar terpintal di sunyi Pamuk
membungkus puing-puing Attaturk
Negeri-negeri salju kastil-kastil kertas
sejarah mengeras di tapal batas
hari-hari timur hari-hari barat
hamba dan tuan bertukar tempat.
Musim mengeras di tapal batas.
Ada yang diam-diam bergegas
melaju di atas seribu bus seperti Pamuk
atau Osman atau Mehmet atau kau
memburu cinta, kematian, atau malaikat
dan tak mendapat apa-apa kecuali
identitas yang meranggas dan sekarat
antara masa kanak yang terkoyak
dan masa depan yang lembam.
Antara timur yang mendengkur
dan barat yang berkarat.
Dari Herat menuju ke Barat
merana tersungkur di Indonesia
ingatan adalah rakyat berkarat
menetas sia-sia dari telur amnesia.
Sambil menyusuri kota kelahiran
dalam ingatan silam, ditentengnya hidup baru
seperti menenteng kopor ayah
tempat istana salju dan buku hitam catatan harian
menyembul diam-diam bagai kenangan:
bacaan-bacaan masa muda
yang menggendong sukma ke Eropa,
dan hikayat-hikayat keramat
yang menuntun gelisah
kembali pulang ke rumah.
Di luar masih terhampar
dunia-dunia yang membenci
sebesar mencinta, yang bercumbu
sekerap bertengkar, bagai hujan salju
yang indah dan memisah hingga selalu susah
untuk bertegur sapa. Tapi akan selalu ada
yang sabar seperti Orhan, menyalakan lilin
untuk mencairkan salju yang membeku
di jembatan perjumpaan
biar segala yang lindap dan tak terucap
dapat bersijingkat temukan jalan.
GORKY
Di sebuah negeri gamang dan pilu
Gorky yang piatu melahirkan seorang ibu
untuk membuka hati dan mengasuh
hari-hari jelata yang rusuh. Bagai Musa
Ia menuntun jelata pekerja
untuk berhijrah dari kubangan vodka.
Di kerontang akar rumputan, kesadaran
konon tumbuh merimbun bagai palawija
berbuah mesra penuh janji
untuk dipanen kelak selepas fajar pagi.
Tapi sejarah selalu milik ayah.
Mereka memanennya malam-malam
hingga tak banyak yang tersisa
di ladang selain warna merah
dari jejak-jejak amarah.
Di lorong gelap jelata, di kedalaman
terbawah, ada pelacur dan pencuri
merayapi mimpi mengharap cerlang matahari.
Dan bangsawan afkiran, buruh harian,
pedagang asongan, sibuk menanam diri
dalam cerita warna-warni
karena sesekali, orang-orang merasa perlu
menyentuh jiwa papa kelabu
dengan sedikit warna ungu.
Dalam gairah, Gorky menyusun
masyarakat dari lembar-lembar kertas
dan penguasa melemparnya ke tungku
biar revolusi berkobar selalu.
Waktu berganti rezim berlalu
di tanah yang merah dan tak merah
semua berubah, kecuali pelaminan
tempat penguasa penuh gairah
menjamin jelata dan kemiskinan
agar senantiasa bisa menikah.
Tinggal Gorky: masai dan terlunta
dijahit penguasa menjadi bendera
berkibar-kibar seperti sejarah
tempat jelata terbungkam pasrah.
Terima kasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat. Baca juga kumpulan puisi Armijn Pane